Meneguhkan Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Ideal di Era Artificial Intelligence (AI)
Oleh: Fatih Madini (Guru Pesantren At-Taqwa Depok)
Artikel Ilmiah
Liputan Kegiatan
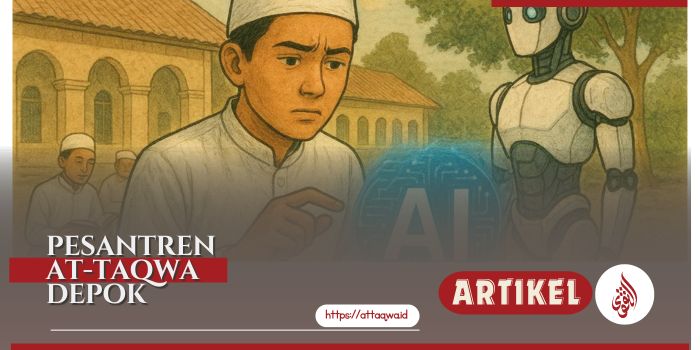
Di masa Politik Etis, penasihat ulung pemerintah kolonial Belanda terkait urusan Muslim-pribumi, Christian Snouck Hurgronje, menyerang umat Islam secara “senyap” melalui melalui lembaga pendidikan sekular. Snouck meyakinkan pemerintah Belanda bahwa “Pendidikan dan pengajaran dapat melepaskan orang Muslimin dari genggaman Islam!”
“Meskipun saya lahir dalam sebuah keluarga Muslim yang taat, dan mendapatkan didikan agama sejak dari masa kanak-kanak, namun (setelah masuk sekolah Belanda) saya mulai merasa kehilangan iman,” tutur The Grand Old Man H. Agus Salim (Yudi Latif, Intelegensia Muslim dan Kuasa, 2021).
Penggagas “Taman Siswa” Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan Belanda bergaya Barat itu sangat mengabaikan aspek “pendidikan”, penanaman nilai, yang menghasilkan “kecerdasan budi pekerti”. Ia hanya mengutamakan pengajaran, pemberitahuan pengetahuan, yang menimbulkan penyakit “intellektualisme”: “mendewa-dewakan angan-angan”.
Darinya, muncul dua penyakit lain: individualisme (kemurkaan diri) dan materialisme (kemurkaan benda). Jiwa pun kering kerontang, kepribadian tak tumbuh, adab tak tertanam. “… itulah yang menyebabkan hancurnya ketenteraman dan kedamaian di dalam hidupnya masyarakat,” tegas Ki Hajar. (Panitia Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Ki Hajar Dewantara, 2013).
Maka dengan penuh keheranan, Ki Hajar mempertanyakan para orang tua yang masih saja memasukkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan yang hanya mengarahkan mereka pada tujuan-tujuan materi semata:
“… anehnya, banyak priyai atau kaum bangsawan yang senang dan menerima model pendidikan seperti ini dan mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah yang hanya mengembangkan intelektual dan fisik dan semata-mata hanya memberikan surat ijazah yang hanya memungkinkan mereka menjadi buruh,” (Adian Husaini, Perguruan Tinggi Ideal di Era Disrupsi, 2019).
Begitulah kemudian pendidikan Barat—di samping keunggulannya dalam mengembangkan aspek kognitif—mengikis iman dan nilai, mengarahkan pada orientasi dunia yang begitu berlebihan sehingga lupa tujuan hakiki hidup manusia untuk bahagia di akhirat dengan bermanfaat dan berjuang di dunia demi agama dan bangsanya.
Dalam rangka membendung arus sekularisasi melalui sekolah-sekolah Belanda dan menghidupkan kembali cahaya Islam, lentera adab dan api perjuangan, para ulama pun mendirikan pesantren-pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk melahirkan generasi pejuang.
Pahlawan Nasional Mohammad Natsir menyebut langkah ulama mendirikan pesantren dalam rangka menghadapi kebijakan politik etis itu sebagai strategi “’Uzlah” yang brilian. Katanya, “pesantren adalah lembaga yang dikembangkan dalam rangka perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, pesantren bukan saja merupakan Lembaga pendidikan, tetapi mempunyai peran yang penting dalam perjuangan nasional” (Natsir, Pesan Perjuangan Seorang Bapak, 2019).
Ki Hajar, dalam artikelnya di Majalah “Wasita” Jilid 1 No. 2 (28 November 1928) berjudul “Sistem Pondok dan Asrama Itulah Sistem Nasional”, pun sangat yakin kalau model pendidikan ala “pondok pesantren” jauh lebih baik dari model pendidikan kaum penjajah.
Pesantren, katanya, dapat benar-benar memaksimalkan aspek “pendidikan” yang menekankan penanaman nilai atau pembentukan pribadi melalui tiga elemen: pawiyatan (asrama), keteladanan guru, dan interaksi intensif dan “24 jam” antara guru dan murid.
“Oleh karena guru-guru dan murid-murid itu tiap hari hidup bersama-sama, siang malam bersama-sama makan, bermain, belajar, bergaul, sudah teranglah di sini anak akan terdidik dengan sempurna, tidak menurut buku-buku pedagogik, tetapi menurut pedagogik yang hidup, yaitu menurut cara hidup yang nyata dan baik. Dengan sistim demikian maka anak-anak kita… terus insyaf akan kemanusiaan, karena senantiasa hidup dalam dunia kemanusiaan… Disitu… pengajaran dengan sendiri selalu berhubungan dengan pendidikan,” jelasnya.
Darinya dapat lahir manusia-manusia yang tidak hanya berilmu (agama dan umum), tapi juga baik, bermanfaat dan mau berjuang dengan ilmu dan fisiknya. Generasi santri yang mau, siap dan bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1945 dari tangan pasukan sekutu (Inggris-Belanda) adalah bukti konkretnya.
Mereka menyambut dengan penuh semangat Resolusi Jihad yang diumumkan KH. Hasyim Asy’ari (22 Oktober 1945) dan Resolusi Perang Sabil (8 November 1945), yang menyerukan “fardhu ‘ain”-nya setiap Muslim mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.
Berduyun-duyun mereka turun ke medan pertempuran. Pasukan Inggris benar-benar dibuat kewalahan bahkan sampai dipermalukan. Jenderalnya, Mallaby, yang juga alumni Perang Dunia II pun berhasil ditewaskan.
“Pekikan takbir ‘Allahu Akbar’ menyatu dengan pekikan ‘Merdeka atau Mati’ di hampir semua front pertempuran… sampai seorang komandan pasukan India (dari pihak Inggris), Zia-ul-Haq, terheran-heran menyaksikan para Kyai dan santri bertakbir sambil mengacungkan senjata. Sebagai Muslim, hati Zia-ul-Haq terhenyuh, dan dia pun menarik diri dari medang perang” (Zainul Milal Bizawie, Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad, 2014).
Kini, relevansi pesantren sebagai lembaga pendidikan Nasional yang ideal, tak perlu diragukan. Setidaknya ada dua alasannya:
Pertama, ia yang paling berpeluang mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional: melahirkan manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan lain-lain, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, UU Sisdiknas, dan UU Pendidikan Tinggi.
Kedua, di era disrupsi dan Artificial Intelligence (AI), di mana mengkaji sebuah teori jauh lebih mudah (karena begitu leluasanya akses internet) ketimbang menjadi seorang “pembelajar” yang cinta ilmu dan semangat menghidupkan budaya ilmu; dan menjadi “pejuang” yang mau mengamalkan dan menyebarkan ilmunya, pesantren punya peran yang begitu signifikan untuk mewujudkannya.
Manusia-manusia pejuang, jujur, disiplin, pekerja keras, amanah, kreatif, mau berpikir kritis, dapat berkolaborasi sampai bijaksana, yang begitu didambakan banyak pihak bahkan pemerintah, demi mengurangi angka pengangguran, dapat diupayakan kelahirannya oleh pesantren secara lebih maksimal.
Islam, memandang penanaman nilai atau adab (termasuk ruh jihad), atau yang sering disebut pula dengan “soft skill”, begitu utama karena punya motivasi tertinggi yaitu akhirat: mempertanggungjawabkan ilmu yang dipunya supaya diamalkan dan diajarkan sehingga bermanfaat bukan malah menjadi penjahat berilmu yang jahat kepada Tuhan dan makhluk-Nya bahkan merusak alam; berjuang demi agama dan bangsa (melalui fisik ataupun pemikiran) terlepas seberapa pun ilmu yang dipunya dan apa pun profesinya, bukan sekadar bercita-cita “supaya bisa kerja”.
Kini, para pakar pendidikan bahkan pemerintah mulai menyadari bahwa soft skill atau yang sering disebut “karakter”, jauh lebih dibutuhkan ketimbang hard skill, sekalipun para mahasiswa diarahkan untuk “supaya bisa kerja” semata.
Artinya, lembaga pendidikan harus mampu menumbuhkan budaya ilmu, membentuk cara berpikir yang baik dan benar, membersihkan jiwa yang kotor, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan perjuangan dalam rangka melahirkan para intelektual, ulama dan guru pejuang.
Ia tidak boleh berubah orientasinya, menjadi lembaga bisnis semata, dengan produk bernama “manusia”. Akhirnya, jiwa para produk-produk itu mengalami tragedi yang begitu hebat. Pasca lulus, tak siap mengabdi pada umat, tak tahu harus ke mana dan melakukan apa, lebih tertarik untuk memenuhi tujuan-tujuan pragmatis dan materialistis.
Begitulah peran pesantren dibutuhkan.